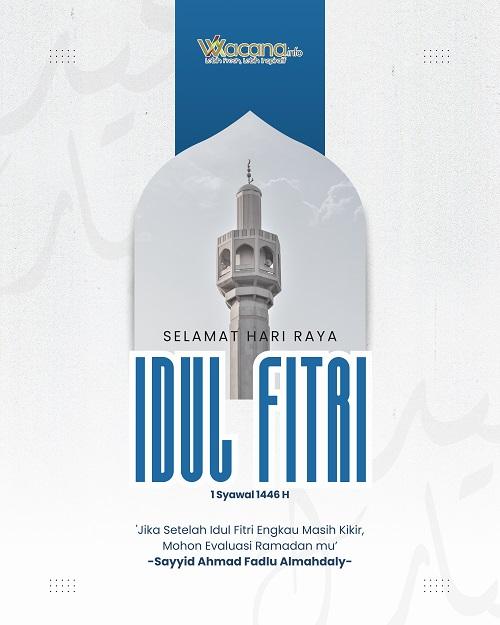Relevansi Tradisi Civill Law dan Judicial Riview di Indonesia

Oleh: Hairil Amri (Ketua Umum IKAMA Sulbar Yogyakarta Periode 2017- 2019), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhyammadiyah Yogyakarta
Hukum Itu bergerak menyesuaikan kebutuhan yang dianggap perlu untuk ditetapkan dan diterapkan. Contohnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 362 tentang pencurian, ternyata juga mengalami dinamisasi.
Sebelumnya, kata mengambil ditafsirkan untuk sesuatu hal yang berwujud dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah mengalami kebuntuan dengan adanya kasus pencurian listrik dan gas (kedua objek tidak mewujud atau tidak terindrai) kemudian mengalami perluasan makna, yakni bukan lagi hanya yang mewujud tetapi juga tidak mewujud selama melekat hak subjek terhadap sesuatu hal.
Begitupun dengan Konsep judicial riview dalam konteks Ke-Indonesiaan (HTN - Hukum Tata Negara) yang dalam lintasan sejarah selalu dikaitkan dengan perlunya lembaga Mahkamah Konstitusi.
Dalam dunia akademis, Hukum Tata Negara (HTN) tidaklah cukup hanya dipandang sebagai suatu objek hukum positif melainkan mesti dipandang sebagai suatu Ilmu, sehingga tidak terkungkung dalam teks bahkan hingga memperdebatkan teks. Tetapi seyogyanya subjek akademis mampu melihat faktor yang melatarbelakangi teks: peristiwa, kondisi, dan perkembangan Ilmu pengetahuan.
Jika memandang HTN hanya sebagai objek Hukum Positif, maka cukuplah hanya membaca teks Pancasila dan UUD 1945. Begitupun sebaliknya, jika subjek akademis memandang HTN sebagai ilmu pengetahuan maka barang tentu dengan membaca teks Pancasila dan UUD 1945 sangatlah tidak cukup. Contoh pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) UUD 1945: untuk mengetahui dan memahaminya tentu tidak cukup dengan hanya menyimak pasal per pasalnya, ayat per ayatnya. Subjek akademis mesti membuka buku yang sama membahas tentang HAM, sehingga kita benar-benar menjadi insan akademis yang komperhensif ilmunya guna menjawab tantangan berhukum kita di masa yang akan datang.
Tentang Sistem Yradisi Civil Law
Lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu negara tidak lepas dari sejarah tradisi (hukum) dan budaya (hukum) - legal culture yang dianut pada masyarakat tertentu. Bagi masyarakat yang menganggap praktik-praktik kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum, maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis sebagai bagian spirit of the people suatu bangsa.
Sebaliknya ketika tradisi dan budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa, maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang dikodifikaisikan.
Berangkat dari analisis sederhana itulah saya saya ingin menyampaikan bahwa lahirnya bermacam - macam sistem hukum di dunia Itu mengikuti tradisi dan budaya masyarakat nya sendiri.
Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa barat, Amerika latin, timur dekat, sebagian besar afrika, Indonesia dan jepang. Sistem hukum ini diturunkan dari hukum Romawi kuno, dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara. Sistem hukum ini juga disebut jus guiritium sebagai lawan sistem hukum jus gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yakni antar negara.
Dalam perjalan waktu, hukum Romawi tersebut kemudian dikompilasikan bahkan dikodifikasikan. Dalam sistem hukum ini dikenal istilah code yaitu Undang-Undang yang dianggap sebagai sumber hukum utama yang lainya menjadi sumber hukum subordinat.
Dengan melihat penjelasan di atas bisa kita liat letak kesamaan antara sistem hukum di Indonesia dengan tradisi hukum Civil Law. Betapa tidak, Belanda menjajah indonesia beratus-ratus tahun yang berimplikasi pada perkembangan sistem hukum di bumi nusantara. Makanya tak heran di Indonesia dewasa ini mempraktikkan hal yang demikian, yakni penerapan setiap aturan dari setiap aspek kehidupan manusia.
Di tingkat nasional, peraturan hukum disebut Undang-Undang (UU), di tingkat daerah peraturan hukum disebut Perda (Peraturan Daerah) sehingga dalam perkembangan hukum di Indonesia yang diawali dari sistem hukum adat atau hukum tidak tertulis bergeser menjadi hukum tertulis atau biasa disebut sebagai positivisme hukum.
Pra kemerdekaan semasa Belanda menduduki Indonesia sebagai jajahan mempraktikkan sistem hukum negaranya, yakni sistem hukum positif. Lihat saja KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai contoh, yang kemudian diterapkan di indonesia pasca kemerdekaan dengan dasar asas konkordansi dalam UUD 1945 yakni pada Pasal II aturan peralihan.
Berdasarkan penjelasan di atas antara sistem hukum indonesia dan sistem hukum Belanda dalam perkembangannya yang pada akhirnya mengalami perbedaan. Dengan adanya mekanisme judicial riview menjadi salah satu faktor pembedanya.
Judicial Riview dalam Perdebatan BPUPKI
Di dalam BPUPKI sewaktu sidangnya ternyata para founding State juga memperdebatkan hal yang demikian. Yakni Soepomo dan M. Yamin. Dua sosok itu memperdebatkan apakah perlu judicial riview diberlakukan di indonesia.
Tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, M. Yamin mengusulkan kira-kira begini: perlunya perluasan wewenang Balai Agung-Mahkamah Agung (sebutan awal MA), yakni berkaitan dengan judicial riview. Ada tiga neraca yang M. Yamin usulkan sebagai tolak ukur pengujian, yakni: UUD 1945, Hukum Islam dan Hukum Adat.
M. Yamin tentu punya pendapat sebagai sebab, mengapa beliau mengusulkan demikian. Dalam beberapa literatur yang saya baca, M. Yamin memikirkan keserasian norma yang ada dalam tubuh sosial-masyarakat kita terhadap suatu aturan atau Undang - Undang.
Namun Dalam persidangan tampaknya Soepomo enggan sepakat dengan pendapat M. Yamin, sebab kata Soepomo sda hal yang sangat prinsiple yaitu: sistem UUD 1945 yang telah disepakati (naskah asli) tidak memungkinkan adanya satu lembaga membatalkan putusan lembaga yang lain, sebab sistem tata negara yang telah disepakati adalah sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan yang dalam naskah asli MPR sebagai Pengejawantahan kedaulatan Rakyat (legislatif heavy).
Selain dari pada itu, alasan prinsiple lainya yakni sistem hukum kita banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Semisal sistem civil law-nya dan asas hukumnya yakni hakim dilarang menilai Undang - Undang dan hanya dibolehkan menjadi corong dari aturan atau melaksanakan setiap aturan. Di luar dari pada alasan-alasan yang prinsiple tersebut, Soepomo juga melihat kuantitas sarjana hukum Indonesia waktu itu yang masih sedikit. Dan hasil dari pada perdebatan tersebut usulan M. Yamin tidak di terima.
Mahkamah Konsatitusi, Pembaharu Civil Law
Dewasa ini Kemajuan sistem hukum di seluruh dunia cukup membanggakan. Betapa tidak, selain dari pada semakin demokratisnya tatanan, juga semakin menjaga marwah manusia sebagai subjek sekaligus objek hukum. Sistem yang satu dengan sistem yang lainya terus berpacu mentransformasikan bentuknya masing-masing, seperti tradisi hukum civil law yang menemukan sistem pembaharuanya melalui lembaga peradilan.
Di beberapa negara termasuk Indonesia juga menerapkan Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga penjaga dan pengawal pemberlakuan konstitusi di masing-masing negara. Sepaham saya, negara pertama di dunia yang menerapkan dan membentuk Mahkamah Konstitusi yaitu Austria, tepatnya di Wina. Kontribusi pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky cukup menjadi rujukan umum mengenai gagasan Mahkamah Konstitusi.
Indonesia setelah mengalami penyesuaian, dengan dasar pengalaman orde baru kemudian memasuki tahap reformasi yang dibarengi dengan Amandemen Konstitusi. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem pembagian kekuasaan bertransformasi menjadi sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balances.
Di tahap inilah naskah konstitusi menjadi berkenyataan. Tidak lagi abstrak dan menjadi naskah yang sangat sakral, elitis dan ekslusif. Sebab dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi di era reformasi, mekanisme judicial riview dari setiap code atau Undang-Undang dapat dapat diuji dalam peradilan. Seperti kata Prof. Satjipto Rahardjo, idealnya hukum tidak Hanya tumpul ke atas. Sebagaimana kewenangan Mahkamah konstitusi, diharapkannya setiap Undang-Undang tidak lagi menindas manusia sebagai subjek sekaligus objek hukum. Bila terdapat hal demikian, silahkan digugat dan dibuktikan, sebab setiap rakyat memiliki posisi sama d imata hukum (equality be for the law).