G30S/PKI, Karya Seni Propaganda, dan Tantangan Para Milenial
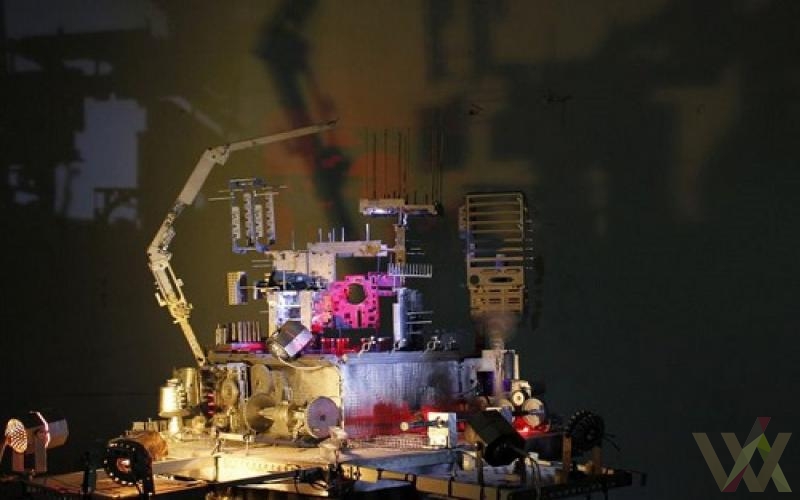
Oleh: Bambang Asrini Widjanarko (Kurator Seni/Kompas.com)
KARYA seni, entah bentuknya berupa lukisan, puisi atau sebuah pementasan opera, ratusan tahun lalu terikat konsep ars imitatur naturam. Adalah upaya manusia untuk mengekspresikan tentang kehidupan dan alam.
Apapun yang disediakan secara natural direfleksikan lugas oleh pikiran-pikiran manusia. Para sarjana tempo dulu menyebutnya sebagai mimesis.
Manusia tak berhenti di sana, karya seni demikian kompleks dimaknai kehadirannya di kemudian hari.
Fenomena sosial-budaya, apalagi kelahiran sains modern membuat seni makin rumit pun majemuk sekaligus sebenarnya makin indah. Sebab, manusia dituntut menggunakan nalar dan intuisinya lebih progresif memaknai arti keindahan dalam seni.
Ada begitu melimpah sumber-sumber kultural yang beragam dari realitas hidup yang membantu memperkaya pemahaman tentang seni.
Sampai kondisi psikis manusianya sendiri yang paling abstrak dan komunitas masyarakatnya mampu digunakan sebagai instrumen menafsirkan atau memproduksi karya seni.
Karya seni tidak lagi meniru hidup apa adanya, apalagi hanya menawarkan pilihan tegas: hitam atau putih saja, yang tepat atau yang tidak tepat saja. Namun ia adalah hasil “maha kompleks” pengalaman-pengalaman manusia.
Konsep mimesis gugur, hadirlah teori dan pendekatan keilmuan lain yang lebih elok menafsirkan seni serta membuka daya jelajah estetiknya.
Karya seni pada abad modern memprovokasi orang berpikir makin tajam, kadang membangun logika saling bertentangan, menguak jurang terdalam eksistensial kedirian manusia sampai menimbang berbagai hal, yang kemudian menggugatnya kembali.
Sebaliknya, karya seni masih bisa kita temukan jenisnya yang menyentuh manusia di batin terdalamnya. Membuat orang-orang menangis terharu, memeluk memori individualnya yang terselimuti narasi-narasi kedamaian. Seni menjadi semacam energi spiritualitas yang memayungi jiwa manusia.
Atau yang paling kontekstual saat ini, pada bulan September, karya seni konon mampu meledakkan ketakutan kolektif dari ideologi yang dianggap mengerikan, di sebuah film bertujuan politik dengan hasil akhir: ketundukan atau pemakluman.
Dari sana, sebuah film propaganda rezim Orde Baru yang menghebohkan jika ditayangkan ulang menarik untuk diulas. Jika dikatakan karya seni ini berhasil, memang telah berhasil menciptakan ketakutan-ketakutan di masa lalu, di era 80-an dengan jutaan pemirsa terhipnotis.
Tapi benarkah kengerian-kengerian itu masih berlangsung sampai hari ini? Belum tentu.
Generasi millenial
Bagi generasi millenial, kutipan dari Picasso, seniman dunia dengan pernyataannya yang terkenal ini pastilah ditimbang, yakni art is the lie that enables us to realize the truth.
Film versi Orde Baru itu memang perlu diuji untuk mewujudkan klaim kebenaran yang disampaikan. Tidak pada masa lalu namun saat ini.
Bukankah, sebuah karya seni adalah hasil dari penafsiran pengalaman-pengalaman majemuk manusia di sebuah waktu, dan di sebuah peristiwa, yang bisa ditelaah kembali pada masa yang akan datang?
Sebuah konstruksi ide dari kenyataan yang bisa benar, bisa juga jauh dari benar nenurut versi lainnya. Tentu jika kita relasikan dengan fakta-fakta historis dan berbagai informasi serta pengetahuan-pengetahuan teranyar.
Dunia kita makin terbuka, makin mudah bagi generasi millenial untuk mengakses masa lampau dengan segala kompleksitas yang mewarnainya melalui e-book, informasi di situs tertentu, media sosial, sampai narasi-narasi baru yang mendalam berbentuk seni, yang beragam, seperti cerpen, puisi, film, seni pertunjukan dan juga digital art, sebagai ajang belajar, membandingkan dengan seni ala rezim Orde Baru tersebut.
Ada banyak sumber bisa kita temukan akurasi-akurasi kebenaran peristiwa tahun 65 yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.
Sebagai salah satu contoh, lima skenario yang saling “berseteru untuk memanggungkan kebenaran“ yang menurut Mary Zurbuchen dengan paper-nya “History, Memory, and ‘The 1965 Incident’ in Indonesia”, di Asian Survey, tahun 2002.
Zurbuchen menyebutkan bahwa, pertama, peristiwa G 30 S adalah murni disutradarai PKI dan seluruh simpatisannya. Kedua, akibat pertarungan internal di tubuh militer. Ketiga, bisa jadi keterlibatan Soeharto mengambil keuntungan personal dari peristiwa “coup d'état”.
Selanjutnya, yang keempat, skenario adanya izin Soekarno pada sekelompok kecil perwira militer yang dikenal dengan “Dewan Jenderal’. Dan yang terakhir, skenario hadirnya operasi intelijen negara asing ingin menggulingkan Soekarno dan melenyapkan masa depan gerakan kiri di dunia ke-3.
Dari sana, sebuah intepretasi seni yang bagus dengan pendekatan instrumentalisme, bahwa seni tidak hanya menyangkut sebuah struktur intrinsik dalam film saja, seperti penokohan, plot, tema maupun segala hal teknis sinematografi yang melekat di dalamnya, namun mengikutkan elemen-elemen eksternal seperti kesahihan historis, kondisi politik kekuasaan pada waktu film dibuat, kondisi kultural sekarang, dll.
Film propaganda
Dengan menimbang lima skenario ala Zurbuchen jika dilekatkan pada pendekatan instrumentalisme, sangat jelas kita ketahui bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI sebuah film propaganda.
Film propaganda itu menghiperbolakan kekerasan simbolik. Sebagaimana yang dikatakan sosiolog Pierra Bourdieau, film propaganda adalah produk kebudayaan yang memiliki peran penting mengonstruksi kenyataan dari kekuasaan, yang dikatakan ampuh merasuk pikiran manusia.
Yang tentunya, film itu menjadi kehilangan keindahan makna reflektifnya yang obyektif, dan menisbikan narasi berbeda yang bisa jadi sama-sama dekat dengan kebenaran sejarah.
Generasi milenial tentunya sangat berhak untuk menafsirkan, memelajari ulang, menyusuri kejanggalan-kejanggalan film tersebut sembari membangun sebuah fiksi baru yang mungkin saja bisa menjadi anagram peristiwa-peristiwa yang terjadi pada september 1965.
Dengan memilih data yang berlimpah dengan merujuk historisitas anyar, di luar apakah ada faham komunisme di sana atau tidak.
Meminjam Newtonian, hukum fisika klasik dasar mengajarkan arti kelembaman sebuah objek dengan istilah inersia. Inersia atau kondisi kelembaman adalah kecenderungan semua objek fisik untuk menolak perubahan jika ditimpa gerak dari luar.
Film tersebut telah nyata-nyata menolak laju zaman. Kecepatan perubahan terjadi di mana-mana, di seluruh dunia.
Seperti kita tahu, faham komunis sudah kedaluwarsa. Ideologi komunisme telah binasa, seiring runtuhnya Tembok Berlin, bubarnya Uni Sovyet dan Pakta Warsawa.
Ironisnya negeri komunis kini lebih lihai membincangkan pertumbuhan ekonomi ketimbang ideologi. Vladimir Putin tidak lagi bersilat lidah soal ideologi, tapi menekankan ekpsor migas, penjualan senjata dan berebut hegemoni kekuatan global.
China, yang diwakili Partai Komunis di Beijing lebih panik saat ekspor melemah dan konjungktur turun, ketimbang saat Kongres Rakyat menghadapi kebuntuan. Meskipun China masih menerapkan sistem satu partai, tapi terus membangun zona ekonomi istimewa di mana-mana untuk menggenjot ekspor.
Malahan, negara ini memberi utang triliunan dollar AS kepada banyak negara, bahkan negara mapan sekalipun.
Satu-satunya negara Asia yang berkeras patuh pada ideologi komunisme adalah Korea Utara. Namun, Kim Jong Un lebih menyukai berebut kekuasaan global, dengan pamer kekuatan rudal nuklirnya ketimbang penguatan ideologi.
Dinasti Kim kini terlihat gamblang tak mementingkan komunisme, yang hanya dipakai senjata menenangkan rakyat yang kelaparan serta miskin. Komunisme jelas-jelas menghadapi senjakalanya pada abad ke-21 ini.
Pada saat sama, daya apresisi seni dari hari ke hari secara alamiah makin meningkat di negeri kita ini. Berbagai komponen bangsa mendukungnya, dari lembaga seni pemerintah yang makin terbuka serta siap dikritik meskipun terkadang reaksioner.
Institusi seni independen memproduksi karya-karya yang berlatar sejarah, serta antusiasnya generasi milenial yang mengakses hajatan seni.
Kemudian, aktivitas-aktivitas selebrasi kantung-kantung komunitas dan artspace yang menayangkan berbagai film dokumenter atau fiksi dari sepenjuru jagat yang merangsang generasi muda mencari tahu sejarah bangsa mereka sendiri.
Dari titik tertentu, imbauan penayangan film yang menuai kontroversi, tapi direstui Presiden asalkan dibuat sesuai zaman, sebenarnya justru mendorong generasi milenial berani memproduksi ulang.
Ide itu menawarkan remake film dengan racikan berbeda. Harapannya, suatu saat, kita akan menyaksikan film yang benar-benar lain tentang G30S/PKI. Kita berharap, merasakan lebih banyak sedapnya daripada ngerinya. (*)
Sumber: Kompas.com




















